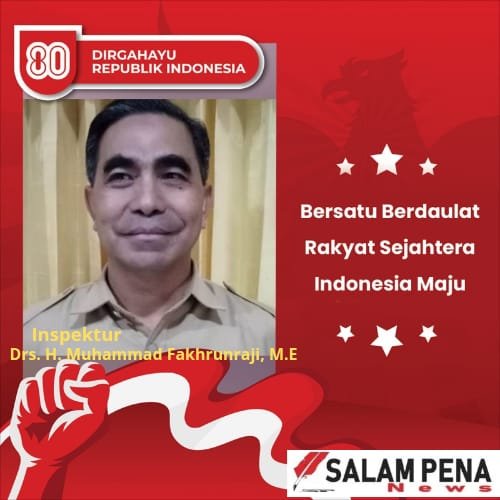Oleh: Agil A-M
Wasekum : PPPA HMI Kom, M. Darwis
Salampena News- Kondisi infrastruktur jalan di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi cerminan buram pengelolaan Dana Desa. Jalan-jalan berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mencerminkan kegagalan tata kelola anggaran. Dana Desa, yang seharusnya menjadi katalis pembangunan, justru memunculkan pertanyaan kritis: ke mana larinya anggaran untuk perbaikan infrastruktur? Ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa di Doridungga bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan pengkhianatan terhadap amanat reformasi desa. Tulisan ini mengkritik tajam buruknya tata kelola Dana Desa, menyoroti pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menawarkan solusi konkret agar anggaran desa benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Pengelolaan Dana Desa di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran (Pasal 27 ayat 2 huruf d). Namun, di Doridungga, kewajiban ini seolah diabaikan. Laporan penggunaan Dana Desa tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, membuat warga terisolasi dari informasi alokasi anggaran—apakah untuk perbaikan jalan, sarana publik, atau justru disalahgunakan. Ketidaktransparanan ini memicu kecurigaan publik dan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Kondisi jalan di Doridungga menjadi bukti nyata ketimpangan pengelolaan anggaran. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Namun, realitas di lapangan bertolak belakang: jalan-jalan tetap tidak layak, membahayakan pengguna, dan menghambat aktivitas ekonomi. Jika Dana Desa dialokasikan sesuai peruntukannya, mengapa infrastruktur dasar seperti jalan tak kunjung diperbaiki? Pertanyaan ini mengarah pada dua kemungkinan: penyalahgunaan anggaran atau ketidakmampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif.
Ketidaktransparanan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengingkaran terhadap esensi reformasi desa. Dana Desa dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan. Namun, di Doridungga, warga dibiarkan dalam ketidaktahuan, tanpa ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Musyawarah desa (musdes), yang seharusnya menjadi forum demokratis untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), jarang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat yang memadai. Akibatnya, warga kehilangan kuasa untuk mengawasi penggunaan anggaran, membuka celah bagi praktik-praktik tidak bertanggung jawab.
Kegagalan ini berdampak luas, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi desa. Ketika jalan tetap rusak meski Dana Desa mengalir setiap tahun, warga mulai mempertanyakan integritas pemimpin desa. Laporan media lokal pada 2021 pernah menyoroti tudingan aktivis bahwa pemerintah desa Doridungga menghindari publikasi laporan keuangan, sebuah indikasi kuat adanya ketidakberesan. Sayangnya, hingga kini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Bima maupun aparat penegak hukum belum menunjukkan tindakan nyata untuk menangani isu ini. Lemahnya pengawasan ini memperkuat persepsi bahwa Dana Desa dibiarkan mengalir tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah tegas yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, pemerintah desa wajib mematuhi kewajiban pelaporan dengan mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa secara terbuka melalui papan informasi desa, situs web resmi, atau media sosial. Kedua, musdes harus diadakan secara rutin dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, untuk memastikan prioritas pembangunan mencerminkan kebutuhan riil warga. Ketiga, Badan Pengawas Desa (BPD) harus berfungsi sebagai pengawas independen, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Keempat, pemerintah kabupaten perlu melakukan audit rutin terhadap penggunaan Dana Desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan anggaran dimanfaatkan secara efektif, terutama untuk perbaikan jalan.
Pendekatan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi inovatif. Pemerintah desa dapat mengadopsi platform digital untuk pelaporan keuangan yang dapat diakses publik secara real-time, meningkatkan transparansi sekaligus memungkinkan warga memberikan masukan langsung. Contoh keberhasilan Desa Gendingan di Ngawi, Jawa Timur, yang memanfaatkan Dana Desa untuk memperbaiki infrastruktur jalan melalui program padat karya tunai, patut ditiru. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan.
Kondisi jalan di Desa Doridungga yang memprihatinkan mencerminkan kegagalan tata kelola Dana Desa. Ketidaktransparanan, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan telah membuat anggaran gagal memenuhi tujuannya: memajukan kesejahteraan warga. Tanpa reformasi mendalam, jalan-jalan di Doridungga akan terus rusak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin terkikis. Pemerintah desa harus membuka diri, mematuhi regulasi, dan melibatkan warga secara aktif. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas, Dana Desa dapat menjadi alat pemberdayaan sejati, bukan sumber kecurigaan.*