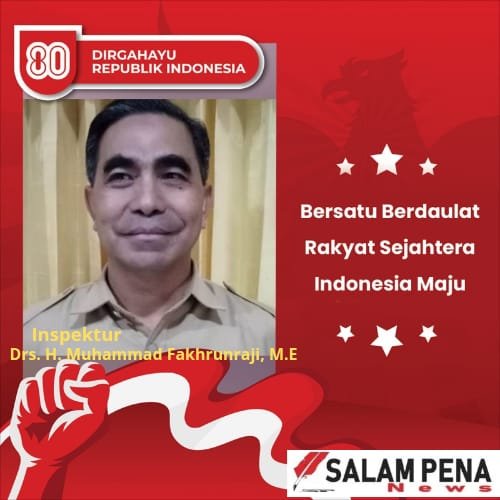Oleh
Luhur Nugroho
Mahasiswa Pascasarjana IPB University, Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika
SOMAHE KAI KEHAGE adalah semboyan yang mengandung arti semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin gigih kita menghadapi tantangan sambil memohon kekuatan dari Tuhan, pasti akan beroleh hasil yang gilang gemilang. Semboyan yang dijadikan motto daerah Sangihe, mental yang seharusnya tertanam disetiap masyarakat Sangihe. Mental yang saat ini harus dimunculkan kembali dalam sebuah “pertarungan” mempertahanan tanah leluhurnya terhadap tambang emas dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe (TMS).
Keinginan pemerintah Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Nusantara menjadi Negara Maritim di dunia adalah cita-cita mulia dalam mengembalikan citra Nusantara yang dahulu menjadi pesona dimata penjajah. Tetapi, visi tersebut perlu dikaji dengan cermat sehingga dapat diimplemtasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kusumastanto (2015), mengutarakan nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejajayaan mariitim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia (Kusumastanto 2015).
Negara Maritim
Pembangunan Negara Maritim memiliki dasar bahwa keberlanjutan pembangunan negara haruslah berdasar pada keberlanjutan bangsa. Kusumastanto (2015), mengutarakan Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, mengusai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara keberlanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Menguasai, mengelola, memanfaatkan dan memperoleh penghidupan dari ekstraksi sumberdaya pesisir dan laut sudah menjadi budaya masyarakat pesisir Pulau Sangihe secara turun menurun dan secara empiris wilayah tersebut sudah pernah mencapai kejayaannya pada masa kolonial Hindia Belanda, sumberdaya kelautan dan wilayah laut yang dimiliki wilayah tersebut telah menjadi modal bagi sebuah wilayah kepulauan yang bervisi sebagai bagian dari wilayah Negara Maritim. Visi Negara Maritim adalah visi kelautan, visi kelautan menurut Kusumastanto (2015) adalah sebuah visi dalam mendayagunakan sumberdaya dan fungsi laut secara berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa.
KOLONIALISME DI UJUNG UTARA INDONESIA,
Kusumastanto (2015) juga mengutarakan bagaimana Strategi Pembangunan Negara Maritim digunakan dalam mewujudkan sebuah Negara Maritim: Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) diharapkan dapat mewujudkan tujuan untuk menjadi negara maritim yang sejahtera. Ocean Policy menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi, maka pembangunan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan nyata yang implentatif melalui Kebijakan Ekonomi Kelautan (Economic Policy), Kebijakan Tata kelola Kelautan (Ocean Governance Policy), Kebijakan Lingkungan Laut (Ocean Environment Policy), Kebijakan Pengembangan Budaya Bahari (Maritime Culture Policy) dan Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy). Penjelasan Prof. Dr. Ir, Tridoyo Kusumastanto, MS. (Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB University) dapat disimpulkan pembangunan keberlanjutan digunakan sebagai alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pesisir.
Dimanakah Keberpihakan Pemangku Kebijakan?
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan PERDA tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara (RZWP3K) Tahun 2017-2037 dengan asas dasar: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, keadilan, dan kebudayaan. Kebijakan pemerintah provinsi tersebut memiliki tujuan: a) Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secara keberlanjutan. b) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. c) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapainya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. d) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Alokasi ruang WP3PK terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, konservasi, strategi nasional tertentu dan alur laut. WP3PK memplotkan wilayah Sangihe sebagai kawasan pemanfaatan umum, zona pemanfaatan umum sendiri mencangkup zona pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertambangan, perikanan tangkap, budidaya, industri, dan fasilitas umum. Kemudian didukung dengan PERDA Kebupaten Kepulauan Sangihe No. 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tentang Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai simpul utama kawasan Nusa Utara selaku pintu gerbang perbatasan Indonesia dari aspek pertahanan dan keamanan serta mengembangkan potensi kelautan yang berwawasan lingkungan sebagai sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Masyarakat atau Rent-Seeking?
Kedua kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintahan Kebupaten Kepulauan Sangihe jika ditinjau secara naskah memiliki tujuan mulia yakni mengedepankan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat, namun pada prakteknya Penataan Ruang Kepulauan Sangihe menampikkan asas RZWP3K -keberlanjutan, peran serta masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan kebudayaan-, tujuan RZWP3K, dan tujuan RTRW Kepulauan Sangihe dalam mengembangkan potensi kelautan berwawasan lingkungan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memplotkan Pulau Sangihe sebagai pemanfaatan umum dengan 56,2% luasan wilayah Pulau Sangihe sebagai wilayah tambang yang kemudian di“amini” oleh Pemangku kebijakan Kepulauan Sangihe dan saat ini diperkuat oleh hadirnya PT. Tambang Mas Sangihe, menampik potensi lain seperti: Pariwisata dan Perikanan Tangkap yang telah menjadi modal alami (sumberdaya) untuk masyarakat Sangihe.
Mengacu RZWP3K Prov. Sulut keseluruhan wilayah Sangihe diplotkan sebagai zona pemanfaatan umum (tambang), RTRW Kep. Sangihe aktivitas tambang hampir mengambil seperempat wilayah Sangihe, dan Area PT. Tambang Mas Sangihe memplotkan 56,2% menjadi target penambangan. Melihat pemetaan wilayah Pulau Sangihe, besar kemungkinan para rent-seeking (pemburu rente) sudah menargetan Pulau Sangihe sebagai wilayah pertambangan sehingga sudah menyusupkan kepentingan mereka melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Rent Seeking
Praktek rent-seeking (pemburu rente) merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek rent-seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson 1982). Selanjutnya, rent-seeking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Ananda 2010). Secara empiris prilaku rent-seeking khususnya pada sumberdaya tambang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar wilayah dan tidak berlandasakan aspek keberlanjutan, cenderung merusak ekosistem yang ada.